Catatan Perjalanan, Kode, dan Demokrasi Munas IGI 2026
19 Jan 2026 - - 1
Bab 1: Kejutan di Gerbang Tingkir

Udara pagi Salatiga masih menyisakan dingin yang menusuk tulang rusuk ketika jarum jam baru saja melewati angka tujuh. Hari itu, Kamis, 15 Januari 2026, bukanlah hari biasa. Ada panggilan tugas yang menggema dari ibu kota: Musyawarah Nasional Ikatan Guru Indonesia (Munas IGI). Sebuah perhelatan akbar tempat para pendidik merajut masa depan.
Diantar sang istri tercinta dengan sepeda motor, aku tiba di gerbang Terminal Tingkir. "Hati-hati ya, Beh. Semoga lancar sampai Jakarta," ucapnya lembut, sebuah doa sederhana yang menjadi bekal terkuatku.
Setelah berpamitan, langkah kakiku menyusuri area keberangkatan terminal. Suasana terminal pagi itu sudah menggeliat. Aku memilih sebuah bangku kosong, duduk santai sambil mengamati hiruk-pikuk penumpang. Waktu seolah berjalan lambat, hingga pukul 08.08 WIB, sebuah bus besar berwarna khas Sinar Jaya perlahan masuk ke pelataran. Hatiku melonjak girang.
"Nah, ini dia busnya," gumamku penuh percaya diri.
Aku bangkit, merapikan jaket, siap menyambut tumpangan. Namun, langkahku terhenti mendadak. Mataku terpaku pada tulisan di kaca depan bus. Bukan Jakarta, bukan Tanjung Priok, melainkan: BANDUNG.
Keningku berkerut. Keraguan menyelinap masuk. Aku memberanikan diri mendekat ke arah kondektur.
"Bukan Mas, ini ke Bandung. Tunggu dulu saja, nanti ada lagi yang ke Priok," jawab sang kondektur ramah.
Aku mundur dengan perasaan campur aduk. Namun, ada satu hal yang tiba-tiba menohok ingatan. Tiket! Selama duduk santai tadi, aku lupa bahwa tiketku masih berupa kode booking di ponsel. Belum dicetak!
"Hampir saja," rutukku dalam hati. Dengan langkah seribu, aku menaiki tangga menuju lantai dua, tempat deretan kios agen berada. Petugas agen Sinar Jaya menyambutku, namun wajahnya menyiratkan sebuah kabar yang tak terduga.
Mataku membelalak. Sleeper Bus? Itu kelas mewah bak hotel berjalan. Sebuah kompensasi keterlambatan yang justru menjadi rezeki tak terduga. Setelah proses cek KTP dan scan tiket selesai, aku turun kembali sambil menenteng sebotol air mineral gratis. Senyum tak bisa lepas dari wajahku. Penantian di Terminal Tingkir yang tadinya membosankan, kini berubah menjadi antisipasi yang menyenangkan.
Bab 2: Kapsul Sunyi di Pantura
Pukul sembilan kurang sedikit. Deru mesin halus memecah lamunan. Bus yang dijanjikan akhirnya menampakkan wujudnya. Gagah, tinggi, dan futuristik. Inilah sang "Sleeper".
Saat pintu hidrolik terbuka, aku disambut aturan yang tak biasa bagi bus reguler. "Sepatu dan sandalnya dilepas di pintu ya, Pak. Silakan dimasukkan ke kresek ini," ujar kru bus dengan sopan.
Aku menurut. Menenteng sepatu masuk ke dalam kabin rasanya seperti memasuki rumah ibadah atau ruang tamu mewah; suci dari debu jalanan. Interior bus membuatku terkesima. Lorong rapi diapit bilik-bilik bertingkat. Tiketku bernomor 12, terletak di lantai satu.

Ini bukan sekadar kursi. Ini adalah kapsul pribadi. Ada bantal empuk, selimut tebal, dan yang paling penting: tirai penuh yang menutup rapat bilik. Aku meletakkan tas, meluruskan kaki, dan menarik tirai. Dunia luar seketika lenyap. Hanya ada aku dan kenyamanan ini.
Bus mulai melaju membelah jalanan Jawa Tengah. Guncangan nyaris tak terasa. Pukul 11.00 WIB, kami berhenti di Rumah Makan Sari Rasa. Tidak ada lagi sobek tiket kertas yang ribet. Cukup pindai QR Code di mesin validasi, dan makan siang prasmanan gratis pun tersaji. Teknologi telah merambah hingga ke sistem istirahat bus malam.
Perjalanan berlanjut. Di dalam bilik kecil yang tertutup tirai itu, aku merenung. Perjalanan lebih dari sepuluh jam ini nyaman secara fisik, namun sunyi secara mental. Terisolasi dalam kemewahan, kesepian perlahan menyapa. Namun, aku menikmatinya sebagai jeda sebelum badai aktivitas di Jakarta.
Bab 3: Bandung Bondowoso Digital di Ibu Kota
Tanjung Priok menyambutku dengan wajah aslinya: keras, remang, dan sibuk. Pukul 19.30 WIB aku menapakkan kaki di terminal. Notifikasi di ponsel berbunyi nyaring, pesan dari grup panitia: "Rapat persiapan akhir dimulai pukul 19.30."
Aku terlambat. Di pelataran terminal, beberapa pria berwajah sangar menghampiri, menawarkan jasa ojek dengan nada memaksa. Aku mengabaikan mereka, menepi ke area terang, dan memesan ojek daring. Motor membelah kemacetan Jakarta Utara, membawaku ke Hotel Grand Dafam. Malam itu habis ditelan diskusi panjang dan strategi acara.
Namun, tantangan sebenarnya datang saat fajar menyingsing. Jumat subuh, sebuah instruksi darurat turun: Tiket masuk Ancol untuk ratusan peserta harus didistribusikan secara digital dan personal. Tidak bisa rombongan.

Waktu tersisa hanya hitungan jam sebelum gerbang dibuka. Sebagai penanggung jawab IT, aku berubah menjadi "Bandung Bondowoso". Laptop dibuka, mata yang masih berat dipaksa awas. Aku tidak bekerja sendiri; aku memanggil Gemini AI sebagai mitra berpikir.
Jari-jemari menari di atas keyboard, merakit baris demi baris kode PHP, membangun database, dan menguji sistem. Adrenalin memacu jantung lebih cepat dari kafein. Dan... berhasil! Sistem siap tepat waktu. Ratusan guru bisa masuk tanpa kendala.
Dengan napas lega, aku memesan taksi daring menuju Hotel Mercure Convention Center Ancol. Di sana, 400 lebih guru hebat dari Sabang sampai Merauke telah berkumpul. Rasa lelah begadang dan koding subuh seketika sirna melihat antusiasme mereka. Munas IGI siap dimulai.
Bab 4: Lautan Guru dan Drama Demokrasi
Ballroom Hotel Mercure Ancol berubah menjadi lautan batik. Cahaya lampu sorot menyapu ruangan megah itu, menandai dimulainya perhelatan akbar Munas. Pembukaan kali ini terasa berbeda: heboh, ramai, namun tetap memancarkan aura berkelas.
Aku berdiri di belakang barisan kursi peserta, sesekali melangkah berpindah tempat sambil menyapa dan berbincang singkat dengan panitia lain. Dari posisi itu, terasa jelas getaran energi yang memenuhi ballroom. Di panggung depan, deretan tokoh penting duduk berjajar—Menteri Luar Negeri, pejabat Kementerian Agama, hingga Gubernur Lemhannas—menegaskan betapa strategisnya posisi organisasi guru ini.

Puncak seremoni terjadi saat Gubernur Lemhannas bangkit dari kursinya. Dengan wibawa yang tenang, beliau meresmikan pembukaan Munas. Tepuk tangan membahana, seolah menggetarkan dinding-dinding hotel di pesisir Ancol.
Namun, bukan hanya para pejabat yang mencuri perhatianku. Mataku justru tertuju ke barisan kursi kehormatan. Di sana duduk para pendiri IGI—para begawan pendidikan. Rambut mereka telah memutih seluruhnya. Salah satunya bahkan telah berusia 89 tahun.
Meski tubuh tak lagi muda, sorot mata beliau tajam dan menyala. Tak ada gurat kelelahan, yang ada hanya semangat murni. Melihat itu, rasa lelahku akibat perjalanan panjang dan kurang tidur karena coding subuh tadi, rasanya menguap begitu saja.
“Kalau beliau yang 89 tahun saja masih sesemangat ini, malu rasanya kalau yang muda mengeluh,” batinku.
Usai seremoni pembukaan, medan tempur yang sesungguhnya dimulai. Sidang pleno digelar, dan peserta dipecah ke dalam kamar-kamar diskusi: Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Untuk memasuki ruang sidang masing-masing komisi, setiap peserta wajib menunjukkan ID Card untuk dipindai oleh petugas di depan pintu. Sistem akan langsung mendeteksi kesesuaian ruang—jika salah masuk, peserta diminta berpindah ke lokasi yang semestinya. Aturan serupa berlaku saat masuk area konsumsi; peserta wajib melakukan pemindaian QR Code agar hak makan tercatat dan tertib. Semua berjalan rapi, terkontrol, dan adil.

Suasana berubah drastis. Jika pembukaan dipenuhi senyum ramah, kini ruang sidang dipenuhi dialektika. Interupsi sahut-menyahut. Nada suara meninggi mempertahankan pendapat. Debat pasal demi pasal berlangsung sengit, namun tanpa permusuhan.
Semua berdebat keras, namun tujuannya satu: demi IGI yang lebih baik. Suasana benar-benar gayeng.

Waktu merayap naik melewati tengah malam. Di luar hotel, angin laut Ancol mungkin sudah dingin menusuk, namun di dalam ruang sidang, suhu tetap hangat oleh semangat. Para pendiri yang sepuh itu masih setia mendampingi, menyimak setiap dinamika hingga larut.
Hingga tibalah puncaknya: Pemilihan Ketua Umum. Atmosfer berubah tegang. Perdebatan tata tertib memanas, bahkan salah satu kandidat beserta pendukungnya memilih walkout meninggalkan ruangan.
Situasi genting. Panitia mengambil keputusan cepat: meninggalkan sistem voting digital, kembali ke manual kertas demi menjaga kepercayaan dan legitimasi.
Proses berjalan lambat dan dramatis. Satu per satu kertas suara dibuka dalam keheningan subuh. Tepat pukul 05.00 pagi, hasil final diperoleh.
Ketua umum petahana terpilih kembali. Palu diketuk. Maraton demokrasi yang melelahkan, panas, dan penuh dinamika akhirnya resmi berakhir.
Bab 5: Solidaritas di Tengah Banjir Jakarta
Tubuhku rasanya sudah remuk redam. Jam di lobi hotel menunjukkan pukul 05.00 WIB. Azan Subuh terdengar sayup-sayup, menandai berakhirnya drama panjang pemilihan Ketua Umum yang menguras emosi hingga dini hari. Mataku berat, tenaga nyaris habis.
“Ayo, istirahat sebentar ke Grand Dafam. Masih ada jeda sebelum penutupan jam sembilan,” ajak Pak Asep, salah satu rekan panitia yang membawa mobil pribadi. Aku mengangguk setuju. Bersama Pak Rahmat, teman sekamarku selama acara, kami segera menuju parkiran.
Mobil melaju perlahan membelah kawasan Ancol yang masih gelap. Namun Jakarta pagi itu sedang murka. Hujan bukan sekadar turun, melainkan tumpah deras disertai angin kencang.
Kami keluar lewat pintu timur Ancol, mengambil arah selatan. Sayangnya, perhitungan kami meleset. Jalanan yang biasanya bisa dilewati kini berubah menjadi sungai cokelat keruh.
Cesss… grrrttt…
Mobil Pak Asep tersedak, lalu mati total di tengah genangan. Mogok. Hanya suara hujan yang menghantam atap mobil. Air sudah terlanjur masuk, membuat mesin tak berdaya.

Air terus naik. Kami terjebak di tengah banjir, dengan kondisi tubuh yang sudah “low battery” setelah begadang semalaman. Aku dan Pak Rahmat saling berpandangan. Tak perlu banyak kata—solidaritas langsung bekerja.
Begitu pintu dibuka—byurr! Air dingin keruh langsung merendam kaki hingga betis. Payung tak banyak membantu, angin terlalu kencang. Dalam hitungan detik, celana dan jaket kami basah kuyup.
Di bawah arahan Pak Asep dari balik kemudi, kami mengerahkan sisa tenaga. Bahu menahan beban mobil, kaki menjejak aspal licin. Napas memburu, tubuh menggigil, namun mobil perlahan bergeser menuju tepi jalan yang lebih aman.

Setelah mobil berhasil dipinggirkan, kami berdiri terengah-engah. Pakaian melekat di kulit, tubuh menggigil hebat. Anehnya, kami justru tertawa kecil. Situasinya terlalu absurd untuk ditangisi.
Dari drama politik di ruang sidang, kami berpindah ke drama fisik bertahan hidup di jalanan Jakarta.
Satu jam berlalu. Hujan mereda menjadi rintik, namun banjir belum surut. Mobil tetap mogok, derek tak kunjung datang. Bajuku yang basah kini terasa seperti es.
Aku mendekati Pak Asep. “Pak, jenengan bajunya kering. Aman nunggu di mobil. Aku sama Pak Rahmat jalan kaki saja ke hotel. Takut sakit. Aku juga harus persiapan pulang ke Salatiga.”
Pak Asep mengangguk maklum. Kami pun mengambil keputusan nekat: berjalan kaki menembus banjir menuju hotel.

Air di beberapa titik setinggi perut orang dewasa. Kami mengangkat tas setinggi mungkin, melawan arus dan sampah yang hanyut. Hingga akhirnya, lobi Hotel Grand Dafam terlihat di kejauhan.
Air hangat di kamar terasa seperti surga kecil. Setelah mandi dan berganti pakaian, aku sarapan seadanya lalu terlelap.
Siang hari, tubuhku menagih harga. Kepala pening, leher kaku, kaki pegal luar biasa. “Masuk angin,” gumamku sambil menelan Paracetamol.
Saat checkout, aku mencoba memesan taksi online.
Grab — Cancelled.
Grab — Cancelled.
Grab — Cancelled.
Tak ada pengemudi yang berani mengambil risiko. Aku menyeret koper keluar hotel, duduk di pinggir jalan dengan cemas.
Seorang pemuda berhenti dengan motor bututnya. “Ojek, Bang?” “Ke Terminal Tanjung Priok. Berani?” “Wani.”

Kami meliuk-liuk masuk gang sempit, perumahan padat dan jalan becek. Jujur, nyaliku sempat ciut. Tapi strategi itu berhasil.
“Salatiga, Mas,” jawabku saat ia bertanya tujuan. “Lho! Aku Solo, Kang!” Suasana langsung mencair. Wong Jawa ketemu wong Jawa.
Di terminal, kami berpisah. “Hati-hati, Kang. Sing sehat.” “Maturnuwun.”
Bus ke Salatiga masih sore nanti. Aku duduk di ruang tunggu, tubuh babak belur, tapi hati terasa hangat. Di tengah banjir dan kekacauan ibu kota, solidaritas dan kemanusiaan tetap menemukan jalannya.
Bab 7: Pulang ke Pelukan Salatiga
(Recehan Dua Puluh Empat Ribu dan Catatan di Ruang Lab)
Langit Tanjung Priok mulai gelap, namun bus Sinar Jaya yang kutunggu tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Hingga akhirnya petugas loket memberi kabar, bus utama tertahan dan aku harus dioper lebih dulu ke Terminal Pulo Gebang.
Aku menurut saja. Tenaga sudah terlalu tiris untuk berdebat. Setelah perjalanan singkat menuju terminal raksasa itu, akhirnya kutemukan bus yang benar-benar akan membawaku pulang.
Begitu tubuhku menyentuh kursi empuk bus malam, tombol shutdown di badanku seolah ditekan otomatis. Lelah akibat begadang saat pemilihan ketua umum, drama banjir, dan mendorong mobil mogok, terbayar lunas. Perjalanan malam itu berlalu seperti kedipan mata.
Aku hanya terbangun sebentar di rest area untuk makan malam dengan mata setengah terpejam, lalu kembali terlelap, diayun lembut oleh suspensi bus yang melaju di Tol Trans Jawa.
Teriakan kru bus memecah mimpiku. Aku tersentak bangun dan melirik jam: pukul 03.00 dini hari. Saat kakiku menapak di aspal Terminal Tingkir, udara dingin menusuk kulit—dingin yang akrab, dingin kampung halaman.
Terminal masih sepi. Beberapa tukang ojek mangkal sambil menunggu penumpang. Salah satu dari mereka menghampiri.
"Ke Argomas, dekat Desa Pendem," jawabku mantap.
Tukang ojek itu menatapku sejenak lalu bertanya, "Berani bayar berapa, Pak?" Aku justru balik tersenyum, "Sampeyan mintanya berapa, Mas?"
"Tiga puluh ribu, Pak."
Aku merogoh saku celana. Dompet sudah tipis, tersisa recehan-recehan sisa perjuangan di ibu kota. Kuhurung semua lembaran uang itu di telapak tangan. Setelah kuhitung cepat, jumlahnya tak sampai tiga puluh ribu.
Tukang ojek itu menatap uang di tanganku, lalu memandang wajahku yang masih menyisakan lelah perjalanan jauh.
"Nggih, Pak. Tidak apa-apa. Monggo naik," jawabnya tulus.
Motor melaju membelah kesunyian Salatiga di pagi buta. Angin dingin menerpa wajah, namun hatiku terasa hangat. Alhamdulillah, rezeki anak saleh, gumamku dalam hati.
Sesampainya di rumah, pintu terbuka dan wajah istriku menyambut. Semua drama banjir, mogok, dan kedinginan di Jakarta luruh seketika saat kakiku menapak lantai rumah sendiri.

Senin pagi aku terbangun sedikit kesiangan. Upacara bendera sudah berlangsung, dan aku tak sempat bergabung. Sebagai gantinya, aku menuju tempat favoritku: Ruang Lab Komputer.
Di ruangan hening penuh perangkat teknologi itu, aku menyalakan komputer dan membuka blog pribadiku. Jari-jemariku menari—bukan merangkai kode program atau sistem pemungutan suara, melainkan merangkai kenangan.
Tentang salah naik bus ke Bandung, kemewahan sleeper bus, ketegangan Munas, drama banjir dan mobil mogok, hingga kebaikan hati tukang ojek sedulur dan ojek tulus di Salatiga.
Sebuah perjalanan dinas yang ternyata adalah perjalanan pulang—pulang ke pelukan kota kecil, ke rumah, dan ke diri sendiri.
— SELESAI —








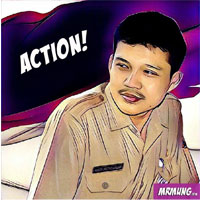








Saya senang menjadi salah satu bagian dari cerita ini. Ditunggu kisah-kisah selanjutnya mister.
BalasHapus